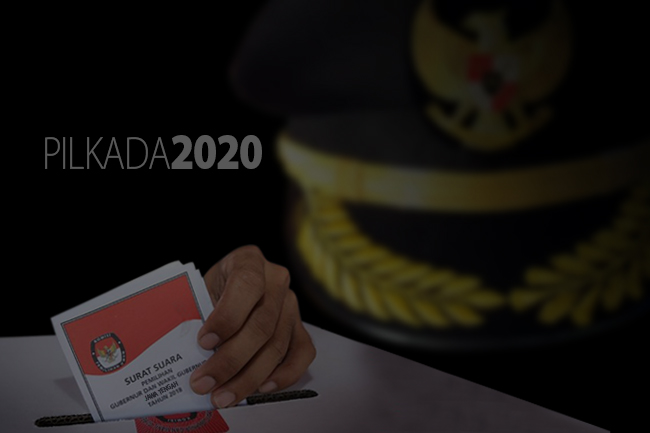
Jakarta, Gatra.com - Tahapan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa pilkada akan jatuh pada bulan Desember tahun ini.
Penundaan Pilkada hanya tiga bulan dari rencana awal yang dijadwalkan pada bulan September. Di tengah pandemi seperti sekarang, koalisi masyarakat mempertanyakan urgensi Pilkada yang tetap dilaksanakan tahun ini. Mengingat, banyak hal yang perlu dikondisikan, dan situasi pandemi yang belum menemui titik terang.
Ketua Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkada Desember mendatang akan memiliki masalah yang kompleks. Pasalnya, pilkada berada di bawah bayang-bayang pandemi, dengan begitu, teknis penyelenggaraan mesti menuntaskan beberapa prakondisi.
Dikatakan, secara global, ada 51 negara yang menunda pelaksanaan pemilu. Namun juga terdapat 8 negara yang tetap mengadakan pemilu. Satu di antaranya yang dipandang cukup berhasil adalah Korea Selatan. Di tengah wabah, partisipasi pemilih justru meningkat sebanyak 8,1%.
"Secara akumulasi naik dari 58% menjadi 66%," kata Jojo pada telekonferensi pers, Ahad (17/5).
Jojo mempertanyakan apakah pemerintah Indonesia, di situasi seperti sekarang, mampu mempertahankan tingkat partisipasi pemilih di wilayah dan daerah. Yang ditakutkan adalah ketika partisipasi masyarakat menurun.
Artinya, pelaksanaan pemungutan suara gagal mengikutsertakan pastisipasi pemilih secara maksimal. Atau dengan kata lain, gagal menghimpun animo masyarakat berpartisipasi dalam pesta demokrasi.
"Di Korsel, teknis pemilu disusun dengan cukup baik, penanganan Covid-19 yang cukup baik, dan kepercayaan kepada penyelenggara negara. Di dalam situasi saat ini apakah penyelenggara, dalam hal ini KPU, cukup dipandang kredibel?" ucap Jojo.
Kesiapan bagi penyelenggara pemilu dinilai kurang. Hal tersebut juga merupakan konsekuensi dari penundaan yang hanya berjarak tiga bulan. Menurut Jojo, besaran waktu tersebut sangat tidak memadai. Karena penyelanggara harus menyiapkan berbagai skema baru yang kontekstual dengan situasi pandemi.
Misalnya, bagaimana dengan mengurai penumpukan massa pemilih di TPS. Bagaimana alokasi anggaran untuk protokol kesehatan di TPS; apakah petugas di lapangan dilengkapi dengan APD, hand sanitizer, dan alat pengukur suhu tubuh.
"Ini akan menambah item di logistik. Implikasinya anggaran yang membengkak. Ini tidak murah," kata Jojo.
Belum lagi, ketika petugas di lapangan menemukan gejala Covid-19 dari peserta. Misalnya, jika ada seorang pemilih yang memiliki suhu 3,75 derajat. Maka, TPS juga memerlukan bilik suara khusus bagi kasus semacam ini. Untuk itu, kotak suara pun akan bertambah. Ini membawa konsekuensi tersendiri. Jumlah TPS bertambah berarti menambah pula jumlah petugasnya.
Selain itu, apakah cukup untuk menyediakan satu tenaga medis di tiap TPS. Jika urusan kesehatan juga dilimpahkan kepada penyelenggara, maka kinerjanya dinilai tidak akan maksimal. Jojo mengatakan, petugas TPS sudah cukup dengan mempelajari bagaimana prosedur pemungutan suara, jangan lagi ditambah dengan beban untuk mempelajari prosedur pengamanan kesehatan.
"Ini menambah kompleksitas penyelenggaraan pilkada. Kita harus mengkontekstualisasikannya dengan kondisi di negara kita," ujar Jojo.





_thumb.jpg)











_(1)_11zon1_thumb.jpg)















